TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia seni pertunjukan, khususnya teater, monolog memiliki kedudukan yang unik dan menantang. Meskipun sering disamakan dengan drama secara umum, monolog memiliki karakteristik yang sangat khas dan membedakannya dari bentuk pentas teater lainnya.
Tidak banyak penulis naskah drama yang juga menulis naskah monolog, karena memang memerlukan pendekatan penulisan dan penghayatan yang berbeda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa Itu Monolog?
Secara etimologis, kata “monolog” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “monos” yang berarti satu dan “logos” yang berarti kata atau ucapan.
Menurut Webster Dictionary, monolog didefinisikan sebagai “drama percakapan seorang diri” atau “pidato panjang”. Dalam konteks teater, monolog adalah sebuah pidato atau dialog yang diucapkan oleh satu tokoh, tanpa interaksi langsung dengan tokoh lain di atas panggung.
Dalam naskah monolog, tokoh-tokohnya dimainkan oleh satu orang pemeran. Pemeran ini bisa berganti-ganti karakter, menjadi dirinya sendiri, menjadi tokoh lain, bahkan menjadi narator.
Dilansir dari artikel The play of Monologue Putu Wijaya, Creative Process and Period of Writing, monolog bersifat satu arah (linear), yaitu penyampaian pesan dari aktor langsung kepada penonton, tanpa dialog dua arah sebagaimana dalam drama konvensional. Meskipun begitu, kadang monolog juga melibatkan tokoh-tokoh imajiner yang hanya ada dalam bayangan aktor, ditampilkan melalui gerak tubuh dan ekspresi seolah-olah ada tokoh lain di atas panggung.
Tantangan dalam Pementasan Monolog
Memainkan monolog bukanlah hal yang mudah. Seorang aktor monolog dituntut untuk menghidupkan berbagai tokoh hanya dengan dirinya sendiri. Ia harus mampu mengekspresikan beragam emosi dan membedakan karakter melalui suara, gestur, hingga tempo bicara. Oleh karena itu, aktor monolog sering dianggap sebagai aktor yang sudah mencapai tingkat kematangan tertinggi dalam seni peran teater.
Tidak semua aktor mampu memainkan monolog dengan baik. Diperlukan “jam terbang” dan kemampuan artistik yang tinggi untuk membuat penonton tetap terpaku sepanjang pertunjukan, meski hanya satu orang yang berbicara di atas panggung.
Putu Wijaya dan Keistimewaan Monolog Karyanya
Salah satu tokoh penting dalam perkembangan monolog di Indonesia adalah Putu Wijaya. Pada tahun 2016, ia menerbitkan buku 100 Monolog Karya Putu Wijaya, yang memuat 118 naskah monolog. Keberhasilan Putu Wijaya menulis begitu banyak monolog tidak hanya mencerminkan kemampuannya, tapi juga menunjukkan proses kreatif yang dalam dan panjang.
Putu Wijaya dikenal dengan gaya penulisan nonkonvensional. Menurut Jakob Sumardjo, Putu menggunakan teknik yang mirip dengan arus kesadaran dalam sastra Barat, di mana alur ceritanya tidak kronologis dan meloncat-loncat dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Meski demikian, ia juga tetap menulis dengan gaya konvensional dalam beberapa karyanya.
Monolog Putu tidak hanya menggambarkan persoalan pribadi atau lokalitas seperti Bali, tetapi juga isu-isu besar di Indonesia, baik pada masa Orde Baru hingga era reformasi. Bahkan saat mengalami stroke, Putu tetap aktif mementaskan monolog seperti dalam pementasan “OH” di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, menunjukkan dedikasinya terhadap dunia teater.
Monolog Tradisional: Ludruk Garingan
Dilansir dari artikel Teater Monolog Tradisional, selain monolog modern, Indonesia juga memiliki bentuk monolog tradisional seperti Ludruk Garingan yang dipopulerkan oleh Markeso pada tahun 1960-an di Surabaya. Dalam pertunjukannya, Markeso tidak hanya memainkan tokoh seorang diri, tetapi juga menirukan suara gamelan secara akapela (dengan mulut), menghadirkan pengalaman menonton yang unik dan menghibur. Pertunjukan ini menjadi representasi kuat dari kekayaan budaya dan kreativitas lokal.
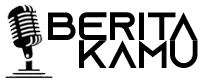


























:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5066824/original/015265300_1735270668-token_listrik_gratis.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4981531/original/087644600_1730043083-UAH.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4857958/original/019677000_1717923099-WhatsApp_Image_2024-06-08_at_22.48.34.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5051207/original/080163400_1734234398-pexels-bertellifotografia-29509460.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4908607/original/070406200_1722691837-lowongan_pegawai_BUMN...jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5060422/original/036311100_1734756382-1734752126842_tips-puasa-sehat-ala-rasulullah.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5078142/original/028454200_1736072896-khabbashasanpendiripon.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3992996/original/032438700_1649747895-WhatsApp_Image_2022-04-12_at_13.14.12__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4596395/original/099329300_1696306947-UAH.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4943958/original/008881100_1726231595-20240913-Kunjungan_Prabowo_ke_Vietnam-AFP_3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3585755/original/069032500_1632814784-muslim-man-using-misbaha-keep-track-counting-tasbih_53876-15256__1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5076649/original/080796900_1735893022-bpjs_kes.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4230261/original/031032400_1668693839-SYAIKHONA_KHOLIL_BANGKALAN.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4741450/original/025950700_1707761166-InShot_20240213_005544283.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4800650/original/039454700_1712990116-WhatsApp_Image_2024-04-13_at_10.15.25__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4710608/original/010580000_1704796503-katemangostar.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3428658/original/001946500_1618390460-WhatsApp_Image_2021-04-14_at_10.58.41_AM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1100203/original/030726300_1451743525-20160101-Kembang-Api-Penjuru-Dunia-AFP-Photo-088.jpg)