TEMPO.CO, Jakarta - Reformasi 1998 telah melahirkan sejumlah kebijakan dan aturan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini, termasuk penghapusan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi bagian suram dalam sejarah Indonesia, di mana terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara besar-besaran yang sekaligus menjadi awal dari berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto dan tumbuhnya semangat reformasi. Dimulai ketika puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang menyerahkan agenda reformasi nasional
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap rezim Soeharto tercermin dalam aksi mahasiswa di depan Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Kerusuhan ini menjadi bagian suram dalam sejarah, dengan korban jiwa empat mahasiswa Trisakti akibat bentrokan dengan aparat. Di antara korban Tragedi Trisakti tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, dan Hendirawan Lesmana.
Kendati menjadi luka dalam catatan sejarah Indonesia, reformasi berhasil membuahkan beberapa produk hukum dan aturan yang dikenal dan dijalankan hingga saat ini, di antaranya sebagai berikut.
Amandemen UUD 1945
Dilansir dari kesbangpol.kulonprogokab.go.id, melihat dampak dari demonstrasi dan Tragedi Trisakti, sidang paripurna diusulkan untuk digelar. Ketua DPR/MPR Harmoko menyatakan bahwa Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju mengadakan sidang paripurna pada 19 Mei 1998, menandakan reformasi semakin dekat.
Setelah reformasi, terjadi amandemen UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, dan kepastian hukum di Indonesia. Reformasi juga membuat Indonesia lebih demokratis dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pemilihan langsung Kepala Daerah, dan munculnya banyak partai politik.
Pemerintah juga mulai menerapkan desentralisasi kekuasaan setelah sebelumnya sangat sentralistik di tangan Presiden selama Orde Baru. Otonomi Daerah memungkinkan daerah mengatur urusannya sendiri dan memajukan daerahnya.
Penghapusan Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI ketika Orde Baru merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Seperti namanya, dwifungsi yaitu selain menjalankan perannya sebagai kekuatan pertahanan di Indonesia, ABRI juga menjalankan tugas sebagai pengatur negara.
Namun, dilansir dari artikel ilmiah Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa karya Azwar dan Suryana (2021), dwifungsi ABRI perlahan dicabut saat reformasi, lantaran dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan oleh oknum militer maupun Soeharto sendiri.
Penghapusan dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berawal dari seminar Angkatan Darat pada 22-24 September 1998 bertema Peran ABRI di Abad XXI. Dalam seminar itu, dihasilkan pemikiran untuk melakukan reformasi dalam tubuh TNI. Kalangan pimpinan TNI pada saat itu memiliki determinasi supaya TNI kembali menjadi tentara profesional sebagai lembaga pertahanan negara.
Karenanya Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal Wiranto, dibantu oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, serta pimpinan TNI lain merasa perlu mengurangi peran TNI dalam politik. Mereka pun secara bertahap menarik diri dari kegiatan politik dan pemerintahan.
Pemisahan TNI dan Polri
Pada masa kepemimpinan Gus Dur, yang sangat pendek (1999-2001), ia juga telah memisahkan Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan TNI.
Sebelumnya upaya pemisahan ini sudah dilakukan sejak bergulirnya reformasi 1998, ketika pemerintahan Orde Baru jatuh dan digantikan dengan pemerintahan reformasi di bawah Presiden B.J. Habibie. Salah satu tuntutan besar masyarakat saat itu adalah pemisahan Polri dan ABRI, dengan harapan agar Polri menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan bebas dari intervensi dalam penegakan hukum.
Presiden Habibie kemudian meresponsnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan pemisahan Polri dan ABRI.
Mendirikan KPK
Dirangkum dari AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah (2015), pada masa kepemimpinan BJ Habibie, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu tuntutan reformasi. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain merilis undang-undang, pemerintah di era Reformasi membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) melalui Keppres Nomor 127 Tahun 1999, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara guna mencegah KKN.
Setelah BJ Habibie, Gus Dur turut mendirikan badan pemberantasan korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun, TGPTPK dinilai tidak bekerja dengan baik, karena menghadapi masalah dalam hal perizinan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.
Sampai akhirnya pada 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk KPK. Setelah dibentuknya KPK, banyak kasus-kasus korupsi yang dibongkar, badan anti rasuah ini bahkan dianggap sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia yang paling berhasil dibandingkan dengan badan-badan sebelumnya.
Pembentukan MK
Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi, setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada 1998 yang menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan hukum. Gagasan Mohammad Yamin ihwal lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau constitutional disputes muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945.
Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April 2000. Awalnya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang.
Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Setelah melewati perdebatan panjang, rumusan mengenai pembentukan MK kemudian diakomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945.
Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Dari sinilah eksitensi MK dalam sistem ketatanegaraan dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.
Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan, MPR menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) akan menjalankan fungsi MK secara sementara, sesuai dengan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.
Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menggagas Rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah menyepakati UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. UU ini kemudian disahkan Presiden Megawati pada hari yang sama.
Pada 15 Agustus 2003, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 untuk mengangkat hakim konstitusi pertama. Pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.
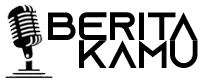






























:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5066824/original/015265300_1735270668-token_listrik_gratis.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3977835/original/066021800_1648524608-pexels-ahmed-aqtai-2233416_1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/4115569/original/096082800_1659876206-Buya_Yahya.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5114856/original/088700500_1738248362-Screenshot_2025-01-30_21.39.48.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5121089/original/029230500_1738678471-dr_Zaidul_Akbar.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5106583/original/012414400_1737616327-BPJS_KKes.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3157041/original/063367600_1592547901-WhatsApp_Image_2020-06-19_at_12.59.18__2_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3317424/original/028829400_1607329507-mehrad-vosoughi-SsKf1L6rWJk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3449231/original/035609000_1620241432-000_99C2L3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1575221/original/040400200_1492996168-islamicitydotorg.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5108842/original/009776100_1737773055-SIM_2025.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4990653/original/076197600_1730716732-tata-cara-sholat-sunnah.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4762786/original/080700200_1709635134-20240305-Pelaporan_SPT-ANG_4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4779768/original/056174500_1711004488-hands-holding-knife-fork-alarm-clock-plate-blue-background.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4990690/original/039762200_1730716919-cara-bayar-fidyah-puasa.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3141448/original/015544800_1591071410-shutterstock_1376538329.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5110589/original/063868900_1737973031-JohnCenaQuran1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5095905/original/084716900_1736950562-logo-harlah-ke-102-nu.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5134530/original/076641900_1739622826-20250215-Prabowo-AFP_7.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/808416/original/069227600_1423479074-gaji-pns-150209b.jpg)