Liputan6.com, Jakarta - Tradisi mencuci kaki dalam pernikahan merupakan bagian dari beberapa adat budaya yang bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan pengabdian.
Dalam prosesi ini, mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria, yang dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap peran suami dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.
Biasanya, ini dilakukan setelah akad nikah sebagai bagian dari rangkaian acara, yang menunjukkan kesiapan dan keseriusan memulai hidup baru bersama.
Dalam sebuah diskusi yang diunggah di kanal YouTube @Pengaosangusbaha, KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha menjelaskan pandangannya tentang prosesi adat mencuci kaki pengantin pria dalam upacara pernikahan. Pembahasan ini diangkat dalam konteks fikih, khususnya dalam ranah adat yang kerap dilakukan masyarakat di berbagai daerah.
Gus Baha mengungkapkan bahwa pernah ada pembahasan khusus atau "bahstul masail" bersama ulama-ulama dari Sarang mengenai hukum mencuci kaki dalam prosesi pernikahan tersebut.
“Saya pernah membahas hal ini dalam diskusi dengan para kiai di Sarang, mengenai bagaimana hukum mencuci kaki pengantin pria dalam upacara pernikahan,” jelas Gus Baha.
Menurut Gus Baha, dalam diskusi tersebut hampir 90% ulama membolehkan tradisi mencuci kaki pengantin pria sebagai bagian dari adat. Alasannya, prosesi ini dianggap sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Meski begitu, ada sekitar 10% ulama yang tidak setuju dengan pandangan tersebut dan berpendapat bahwa praktik itu termasuk bid’ah.
Simak Video Pilihan Ini:
Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang - Video Amatir
Ulama Umumnya Membolehkan
“Secara umum, kebanyakan ulama memperbolehkan karena dianggap sebagai adat yang tidak melanggar syariat. Namun, sekitar 10% berpendapat bahwa ini bid’ah,” tutur Gus Baha dalam videonya. Ia sendiri mengakui setuju dengan fatwa dari kelompok yang 10% tersebut.
Gus Baha menjelaskan lebih lanjut alasan pandangan dari kelompok yang menganggap mencuci kaki sebagai bid’ah. Salah satu argumentasinya adalah bahwa tindakan mencuci kaki lebih relevan dilakukan saat seseorang pulang dari sawah atau tempat yang kotor. Sebaliknya, dalam prosesi pernikahan, kaki pengantin pria sebenarnya sudah bersih.
“Kalau niatnya membersihkan kaki, maka hal itu lebih masuk akal dilakukan saat seseorang baru pulang dari sawah. Tapi kalau kakinya sudah bersih, lalu dicuci, ya itu dianggap hanya sebagai bentuk pamer,” jelas Gus Baha.
Dalam pandangan ini, prosesi mencuci kaki dianggap sekadar menunjukkan atau "riya" karena dilakukan di depan umum. Menurut Gus Baha, jika benar-benar ingin mencuci kaki sebagai bentuk kesetiaan, seharusnya hal itu dilakukan ketika kakinya memang kotor, bukan saat sudah bersih.
Selain itu, Gus Baha juga menambahkan bahwa mengartikan prosesi mencuci kaki sebagai simbol kesetiaan atau bentuk penghormatan hanya sekadar penafsiran yang sebenarnya tidak terlalu relevan jika dilakukan dalam keadaan kaki bersih. Ia menyatakan bahwa niat dari prosesi tersebut penting untuk dipertimbangkan.
Meski memiliki pendapat berbeda, Gus Baha tetap menghargai pandangan mayoritas ulama yang menganggap prosesi tersebut sebagai bentuk adat yang masih bisa diterima dalam syariat. Baginya, perbedaan pandangan ini merupakan bagian dari keragaman pendapat dalam fikih.
Pahami Tradisi Ini
Menurutnya, setiap orang sebaiknya mempertimbangkan pandangan ulama yang paling sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun, Gus Baha lebih cenderung menyetujui pandangan bahwa mencuci kaki pengantin pria dalam upacara pernikahan sebagai bentuk bid’ah.
Gus Baha menjelaskan bahwa praktik adat yang sudah mendarah daging di masyarakat terkadang bisa dimaknai sebagai simbol tertentu, meskipun sebenarnya makna tersebut tidak selalu sejalan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa adat bisa saja dianggap tidak berdosa, tetapi harus diperhatikan niat di balik pelaksanaannya.
Ia mengingatkan bahwa niat menjadi hal utama dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Jika niat mencuci kaki itu hanya sekadar untuk ritual tanpa dasar yang jelas, maka ia termasuk bid’ah. “Intinya adalah niat. Kalau hanya sekadar pamer atau riya, itu yang tidak baik,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Gus Baha memberikan contoh bahwa segala bentuk adat yang tidak memiliki dasar agama perlu dilihat secara kritis, khususnya dalam upacara pernikahan. Ia menyebutkan bahwa pernikahan seharusnya difokuskan pada makna ikatan yang sakral, bukan pada ritual tambahan yang tidak substansial.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu kaku dalam melaksanakan prosesi adat. Jika memang suatu adat tidak menambah nilai ibadah, maka sebaiknya tidak perlu diterapkan secara berlebihan. Gus Baha berharap masyarakat dapat membedakan antara ajaran agama yang murni dengan tambahan tradisi yang sifatnya opsional.
Di akhir pembahasannya, Gus Baha berpesan agar setiap orang lebih berhati-hati dalam mengikuti prosesi adat yang tidak memiliki dasar syariat. Menurutnya, memahami perbedaan antara ajaran agama dan adat dapat membantu seseorang menjalani pernikahan dengan lebih bermakna.
Gus Baha menyarankan agar prosesi pernikahan difokuskan pada kesakralan akad nikah serta perjanjian yang dibuat di hadapan Allah. Baginya, upacara pernikahan yang benar adalah yang lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan etika.
Pada akhirnya, Gus Baha menekankan pentingnya memahami tradisi dalam konteks agama tanpa melanggar prinsip syariat. Dengan demikian, seseorang dapat menjalankan prosesi adat dengan lebih bijak tanpa harus terjebak dalam hal yang dianggap bid’ah.
Penulis: Nugroho Purbo/Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul
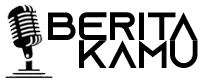
 4 days ago
6
4 days ago
6
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4181555/original/055296900_1664954097-064843300_1649264825-man-praying-alone-divinity-home.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4921601/original/026319300_1723999859-WhatsApp_Image_2024-08-18_at_23.46.19.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4857107/original/037916200_1717822427-WhatsApp_Image_2024-05-26_at_19.19.37.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4424328/original/052701000_1683812394-Buya_Yahya_3.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4975939/original/022263400_1729575541-4dcf7b14-a76d-4fae-96c6-c186248b1020.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4808277/original/050922400_1713720035-WhatsApp_Image_2024-04-21_at_23.53.16__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4517144/original/069576900_1690507869-UAH.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4802318/original/004401300_1713190326-WhatsApp_Image_2024-04-15_at_17.08.40.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4800650/original/039454700_1712990116-WhatsApp_Image_2024-04-13_at_10.15.25__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4857959/original/025768200_1717923099-WhatsApp_Image_2024-06-08_at_22.48.35.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4865196/original/068763100_1718529948-Screenshot_2024-06-16_16.19.23.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3340735/original/052819000_1609831879-WhatsApp_Image_2021-01-05_at_14.17.33__10_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4900936/original/068623100_1721882582-WhatsApp_Image_2024-07-25_at_11.41.22.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4871636/original/050456500_1719070081-Habib_Novel_Alayrdurs_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1181127/original/081971000_1458738090-nuh2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4217763/original/035615200_1667820307-bacaan-tahiyat-awal-dan-akhir-lengkap-dengan-cara-arti-hingga-tujuan-sholat.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1790764/original/084342400_1512450976-20171204VYT_Liga_Remaja_UC_News_15.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4935113/original/024084000_1725336335-image_123650291_1442_.JPG)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/4741587/original/037405400_1707793419-20230213BL_Bhayangkara_FC_Vs_SuwonFC__1.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4823989/original/062289000_1715049774-WhatsApp_Image_2024-05-07_at_09.21.52.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4932413/original/033408200_1725003307-shutterstock_2109839063.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4725538/original/010348100_1706107047-Screenshot_2024-01-24_212658.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4962284/original/095893500_1728302386-undian_BRI_hoaks.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4952817/original/028579300_1727255235-hoaks_freeport.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4780370/original/039195200_1711038401-Screenshot_2024-03-21_23.19.10.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4922582/original/026721500_1724079581-Gus_Baha_dan_Ning_Winda_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4807597/original/046967400_1713623554-Gus_Baha...okk.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4878675/original/083177800_1719647862-WhatsApp_Image_2024-06-28_at_23.25.14.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4730617/original/089869400_1706634490-InShot_20240130_235931572.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4546775/original/061046100_1692679046-man-stands-front-giant-angel-s-wings.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4950020/original/065541500_1726981177-20240922-Sosialisasi_Bawaslu-MER_4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4796571/original/011106700_1712411739-Ilustrasi_orang_tua_dan_anak__minta_maaf__berpelukan__dukungan.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4786884/original/087487500_1711549746-Gus_Baha...ok.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4930324/original/015192200_1724830394-Ilustrasi_ziarah__makam__kuburan__dukacita.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4969269/original/069012300_1728964290-cek_fakta_fifa.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4955119/original/034534200_1727484903-Gus_Baha..ok.jpg)