Liputan6.com, Jakarta - Masuknya Islam ke Indonesia sudah diidentifikasi pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, ditandai oleh kontak perdagangan awal antara pedagang Arab, Persia, dan Cina. Akan tetapi secara massif, masjid baru berkembang secara massif di masa selanjutnya dengan dibuktikan berbagai situs, salah satunya adalah masjid.
Peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah (PR APS) BRIN, Libra Hari Inagurasi, mencermati eksistensi masjid kuno sebagai bagian penting dari sejarah peradaban Islam di Nusantara. Karakteristik umum arsitektur masjid kuno ini.
"Salah satunya atap tumpang/limasan bertingkat tiga atau lebih, sebagai ciri tradisional Nusantara," katanya, dikutip dari laman BRIN.
Khusus di Jawa, perkembangan Islam secara massif tak lepas dari kiprah Walisongo, yang sebagian besar mengedepankan dakwah dengan pendekatan budaya lokal. Itu sebab, arsitektur masjid kuno di Jawa memperlihatkan akulturasi budaya Arab-Jawa yang kental.
Berikut ini adalah ulasan lima arsitektur masjid kuno di Jawa, melansir berbagai sumber.
1. Masjid Saka Tunggal Banyumas
Menurut Andika Saputra dalam bukunya, buku Arsitektur Masjid: Dimensi Idealitas dan Realitas, kekhasan masjid di Indonesia adalah hasil dari dinamika idealitas dan realitas, di mana Islam beradaptasi dengan keragaman budaya Nusantara, menghasilkan arsitektur yang unik dan inklusif.
Berikut ini adalah arsitektur Masjid Kuno di Jawa:
Masjid Saka Tunggal Banyumas
Masjid Saka Tunggal berlokasi di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal diyakini adalah masjid tertua di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, merujuk tahun pembuataannya, sekitar abad 13, tepatnya tahun 1288 M atau 1871 M.
Merujuk Jurnal Pengaruh Budaya Terhadap Tipologi Masjid Saka Tunggal Cikakak Banyumas oleh Amin Safa'at, masjid ini adalah representasi unik dari Islam dan budaya lokal. Menurut Amin, budaya Banyumas secara mendalam tercermin dalam desain masjid ini, dengan penerapan material lokal seperti ijuk, bambu, dan bata
Ciri khas arsitektur Masjid Saka Tunggal terletak pada bangunan utama didukung oleh satu tiang tunggal (saka tunggal) dari kayu jati utuh yang besar, simbol kekokohan dan kesederhanaan. Atap limas bertingkat tanpa kubah, dengan struktur kayu sederhana yang mencerminkan gaya arsitektur Jawa tradisional.
Dinding bata merah dan serambi terbuka, tanpa ornamen berlebih, tetapi memiliki elemen ukiran sederhana pada tiang dan pintu. Tidak ada menara tinggi; fokus pada kesatuan struktur tunggal yang unik di antara masjid kuno Jawa.
Saka tunggal melambangkan tauhid (keesaan Tuhan) dan kesederhanaan hidup, mencerminkan nilai-nilai Islam yang menyatu dengan kearifan lokal Banyumas. Masjid ini menjadi simbol ketahanan budaya di tengah perubahan zaman, sering dikaitkan dengan cerita mistis tentang kekuatan tiang tersebut yang konon tak bisa dipindahkan.
Masjid Saka Tunggal adalah sebuah bangunan historis yang sangat menarik karena menggabungkan nilai agama, budaya lokal Jawa, dan arsitektur tradisional dalam satu kesatuan unik. Tiang tunggal yang menonjol bukan hanya sebagai elemen konstruksi tetapi juga simbolik, menunjukkan bagaimana arsitektur bisa berefleksi terhadap makna hidup dan keimanan.Meskipun ada ketidakpastian dalam detail-sejarahnya (termasuk tanggal pasti), nilai khazanah budaya dan keunikan arsitekturalnya menjadikannya layak untuk dikunjungi dan dipelajari lebih lanjut.
2. Masjid Agung Demak
Masjid Agung Demak berlokasi di Kota Demak, Jawa Tengah. Masjid ini ini cukup populer karena diziarahi lantaran statusnya sebagai masjid berkumpulnya Walisongo.
Masjid ini dibangun tahun 1474 dengan gaya khas Majapahit, yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah.
Hal ini merujuk pada Lawang Bledek yakni pintu utama Masjid Agung Demak. Di hiasan pintu ini terdapat candrasengkala berbunyi “haga mulat salira wani”. Dari sini kemudian ditarik kesimpulan bahwa peletakan batu pertama oleh Raden Patah dilakukan pada 1477 M. Tahun 1479 M.
Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan pada masa awal perkembangan Islam di Jawa. Keunikan utama masjid ini adalah arsitektur masjid yang merupakan akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu-Budha, serta Islam yang terpadu dalam rancangan arsitekturnya.
Atap masjid yang berbentuk tumpang mirip punden berundak menunjukkan pengaruh budaya lokal prasejarah di Indonesia. Bentuk atap yang tumpang merupakan ciri arsitektur Jawa kuno yang juga memiliki dimensi spiritual.
Atap tumpang ganjil yang berjumlah antara tiga hingga sebelas tingkat mengadopsi gaya atap meru khas pura Hindu. Bentuk segitiga atap ini melambangkan persemayaman dewa dalam kepercayaan Hindu, sehingga masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi manifestasi dari persilangan budaya.
Aspek Islam terlihat dari fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah serta ornamen-ornamen yang disematkan, yang menegaskan identitas Islam pada bangunan tersebut.
Merujuk buku Oas Menjelajah Masjid - Masjid Agung Demak karya Agus Maryanto dan Zaimul Azzah, masjid kuno ini memiliki pagar keliling, ruang utama yang berdiri di atas fondasi berdenah bujur sangkar, serta serambi dan kolam yang melingkupi area depan dan sisi kanan-kiri. Mihrab sebagai tempat imam sholat, dan pawestren untuk jemaah perempuan, menjadi bagian integral masjid. Atap masjid yang berbentuk tumpang dengan puncak mustaka melengkapi ciri khas bangunan ini.
Atap limas bersusun tiga pada Masjid Agung Demak melambangkan akidah Islam yang terdiri atas Iman, Islam, dan Ihsan. Tiang utama atau saka guru masjid ini dibuat oleh para Walisongo, tokoh penyebar Islam di Jawa, yakni Sunan Bonang, Sunan Gunungjati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga yang masing-masing menempatkan tiang di arah tertentu.
Masjid ini memiliki lima pintu simbolisasi Rukun Islam, dan enam jendela yang merujuk kepada Rukun Iman. Serambi yang berukuran 30x17 meter berfungsi sebagai ruang sholat dan area pertemuan, yang ditopang oleh delapan tiang utama kayu jati berukir serta dua puluh empat pilar bata dengan motif khas seperti motif daun sulur dan tumpal.
Dengan elemen-elemen tersebut, Masjid Agung Demak mencerminkan bagaimana arsitektur tidak hanya menjadi aspek fisik bangunan tetapi juga sebuah medium ekspresi keagamaan, sosial, dan budaya yang harmonis.
3. Masjid Menara Kudus
Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa Menara Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus, yang bernama asli Ja’far Shadiq, salah satu dari Walisongo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa.
Berdasarkan catatan prasasti yang terdapat di kompleks masjid, bangunan ini berdiri pada tahun 956 Hijriah atau sekitar 1549 Masehi. Masjid Menara Kudus dibangun pada masa awal berkembangnya Islam di Jawa.
Pada saat itu, masyarakat Kudus masih kental dengan budaya dan kepercayaan Hindu-Buddha. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan pendekatan toleran dan akulturatif — yakni menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima masyarakat.
Keunikan utama arsitektur masjid ini terletak pada menara bata merah yang menjulang di bagian depan. Menara ini menjadi ikon khas dan sekaligus identitas kota Kudus. Bentuknya menyerupai candi Hindu-Jawa, terdiri dari tiga bagian utama: kaki, badan, dan puncak, sebagaimana struktur arsitektur candi pada umumnya.
Menara setinggi sekitar 17 meter ini terbuat dari bata merah tanpa semen, dan dihiasi dengan 32 piring keramik dari Tiongkok berwarna biru, merah, dan putih sebagai ornamen dindingnya. Pada puncak menara terdapat tempat khusus untuk bedug, yang dahulu digunakan sebagai penanda waktu shalat, menggantikan fungsi menara azan ala Timur Tengah.
Di dalam kompleks masjid terdapat gapura paduraksa atau gerbang kembar yang bentuknya juga menyerupai gerbang candi peninggalan Hindu. Gerbang ini menghubungkan halaman depan dengan area utama masjid. Di sekitarnya juga terdapat delapan pancuran air wudhu, yang melambangkan “Asta Sanghika Marga”, delapan jalan kebenaran dalam ajaran Buddha , sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya masyarakat setempat.
Bangunan utama masjid memiliki atap bertumpang tiga (tajug), khas arsitektur Jawa, yang melambangkan tiga tingkatan iman: Islam, iman, dan ihsan. Tiang-tiang penyangga dari kayu jati besar menopang ruang utama. Di dalamnya terdapat mihrab dan mimbar yang sederhana, menonjolkan kesan klasik dan spiritual.
Keseluruhan kompleks masjid ini menunjukkan perpaduan harmonis antara unsur Islam, Hindu-Jawa, dan Tionghoa.
4. Masjid Agung Cirebon (Sang Cipta Rasa)
Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia, terletak di kompleks Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1480 Masehi, pada masa penyebaran Islam di Jawa.
Pendirian masjid ini diprakarsai oleh Sunan Gunung Jati dan istrinya, Nyi Mas Ratu Pakungwati, karena pada masa itu umat Islam di Cirebon semakin banyak dan memerlukan tempat ibadah yang lebih besar dan representatif.
Nama “Sang Cipta Rasa” memiliki makna filosofis yang dalam. Kata Sang melambangkan keagungan Tuhan, Cipta berarti proses penciptaan atau pembangunan, sedangkan Rasa berarti penghayatan dan penggunaan. Jadi, secara keseluruhan, nama itu menggambarkan masjid sebagai tempat suci yang dibangun untuk digunakan dan dihayati maknanya oleh umat manusia.
Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa sarat nilai sejarah dan simbolisme Islam-Jawa. Gaya bangunannya memperlihatkan pengaruh kuat Majapahit dan Demak, terlihat dari bentuk bangunan yang sederhana tanpa kubah, serta penggunaan atap tajug bertumpang tiga — bentuk khas arsitektur masjid tradisional Jawa.
Ruang utama masjid dapat dimasuki melalui sembilan pintu, yang masing-masing melambangkan sembilan Wali Songo, simbol penyebar Islam di tanah Jawa. Di dalam ruang utama terdapat mihrab dengan ukiran bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Ukiran ini melambangkan kesucian dan pencerahan spiritual.
Lantai masjid memiliki tiga ubin khusus yang melambangkan tiga pokok ajaran Islam: Iman, Islam, dan Ihsan. Konon, ubin-ubin tersebut dipasang langsung oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga, menjadikannya memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat setempat.
Pada bagian beranda, terdapat sumur tua yang dikenal dengan nama Banyu Cis Sang Cipta Rasa. Sumur ini dipercaya memiliki air yang membawa keberkahan dan sering digunakan jamaah untuk berwudhu. Bentuk sumur serta area sekitarnya memperlihatkan gaya bangunan batu bata merah tanpa semen, ciri khas konstruksi masa Majapahit.
Keunikan lain dari arsitektur masjid ini adalah ketiadaan mustaka atau kubah pada puncak atapnya. Hal ini menunjukkan pendekatan lokal yang mengutamakan bentuk tajug (atap bersusun) sebagai lambang hubungan manusia dengan Tuhan: semakin tinggi susunannya, semakin dekat makna spiritualnya.
Masjid Agung Sang Cipta Rasa tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga merupakan simbol akulturasi budaya antara Islam dan tradisi lokal Jawa Barat. Setiap elemen bangunan; dari pintu, ukiran, hingga bentuk atap, memuat makna filosofis yang mendalam. Masjid ini menjadi contoh bagaimana ajaran Islam dapat menyatu dengan budaya setempat tanpa menghilangkan jati diri lokal.
Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan dakwah sejak masa Wali Songo. Hingga kini, masjid tetap ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai daerah, baik untuk beribadah, menimba sejarah, maupun berziarah ke makam Sunan Gunung Jati yang terletak tidak jauh dari sana.
5. Masjid Sunan Ampel
Masjid Agung Sunan Ampel berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini dibangun pada tahun 1421 oleh Raden Achmad Rachmatulloh yang tak lain adalah Sunan Ampel.
Masjid Sunan Ampel dirancang dengan gaya arsitektur Jawa kuno yang berpadu harmonis dengan nuansa Arab. Selain kedua unsur tersebut, bangunan ini juga memperlihatkan pengaruh budaya lokal serta peninggalan Hindu-Buddha, sehingga menjadikannya contoh nyata akulturasi budaya dalam arsitektur Islam Nusantara.
Bangunan utama masjid berdiri kokoh dengan 16 tiang besar dari kayu jati. Setiap tiang memiliki panjang sekitar 17 meter dan diameter 60 sentimeter, dibuat tanpa sambungan — sebuah teknik pertukangan tradisional yang menunjukkan keahlian pengrajin masa itu. Panjang 17 meter ini memiliki makna simbolis, menggambarkan jumlah total rakaat salat wajib dalam sehari, sehingga menyatukan nilai artistik dan spiritual dalam satu bentuk arsitektur.
Di sekeliling masjid terdapat 48 pintu dengan lebar sekitar 1,5 meter dan tinggi dua meter. Bentuk pintu yang melengkung di bagian atasnya mencerminkan pengaruh arsitektur Arab klasik, memberikan kesan megah sekaligus sakral pada bangunan.
Atap masjid memperlihatkan ciri khas arsitektur Majapahit, berupa atap tajug berbentuk limas bujur sangkar bertumpang tiga seperti piramida bersusun. Dalam budaya Jawa kuno, bentuk ini disimbolkan sebagai gunung suci, tempat yang dianggap paling dekat dengan Sang Pencipta. Makna filosofis ini kemudian diadaptasi dalam konteks Islam, sebagai lambang keagungan dan ketundukan kepada Allah.
Mengutip jurnal Ornamen Masjid Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Sendang karya Budiono, dkk, kompleks Masjid Sunan Ampel juga dilengkapi dengan lima gapura paduraksa. Kelima gapura tersebut dibangun berdasarkan urutan rukun Islam, yakni:
Gapura Panyeksen – melambangkan syahadat,
- Gapura Madep – melambangkan salat,
- Gapura Ngamal – melambangkan zakat,
- Gapura Poso – melambangkan puasa, dan
- Gapura Munggah – melambangkan ibadah haji.
Setiap gapura memiliki makna spiritual tersendiri, menggambarkan tahapan perjalanan keislaman seorang mukmin.
Selain struktur dan bentuknya, ornamen-ornamen yang menghiasi kompleks Masjid Sunan Ampel juga memiliki nilai seni tinggi. Motif-motifnya diadaptasi dari kesenian tradisional Jawa dan dipadukan dengan gaya Majapahit pra-Islam, seperti simbol Surya Majapahit yang merepresentasikan cahaya dan keagungan.
Ornamen tersebut menunjukkan bagaimana Islam di Jawa berkembang dengan menghormati warisan budaya sebelumnya, namun memberi makna baru yang sesuai dengan nilai-nilai tauhid.
People Also Ask:
1. Ciri arsitektur masjid kuno di Indonesia?
Beberapa karakteristik umum salah satunya atap tumpang/limasan bertingkat tiga atau lebih, sebagai ciri tradisional Nusantara. Bangunan panggungnya terdapat pada wilayah pesisir atau tepi sungai. Sementara material terbuat dari bahan kayu lokal seperti jati, bambu, dan batu bata.
2. Apa masjid tertua di Pulau Jawa?
Masjid tertua di Jawa yang sering disebut adalah Masjid Agung Demak yang didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Fatah bersama Wali Songo. Namun, ada juga masjid lain yang diklaim lebih tua berdasarkan penemuan dan penanggalan arkeologis, seperti Masjid Pesucinan di Gresik, yang diyakini merupakan peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim dari abad ke-14.
3. Bagaimana arsitektur masjid dalam bahasa Jawa?
Ciri khas arsitektur Islam Jawa meliputi atap bertingkat, gerbang upacara, empat tiang pusat yang menyokong atap piramida yang menjulang tinggi, dan berbagai elemen dekoratif seperti puncak atap dari tanah liat yang rumit .
4. Apa yang menjadi ciri khas arsitektur masjid yang dibangun pada masa awal Islam di Nusantara?
Arsitektur masjid pada masa awal kedatangan Islam selalu memiliki atap yang bersusun dan berjumlah ganjil.
5. Apakah nama masjid tertua di tanah Jawa yang dibangun pada abad ke-15?
Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para Walisongo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
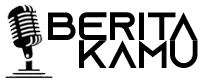
 15 hours ago
4
15 hours ago
4
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/promo_images/1/original/085223300_1761037787-Desktop_1280_x_190.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3433039/original/088234500_1618812222-happy-arab-woman-hijab-portrait-smiling-girl-posing-green-studio.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1606241/original/080046800_1495859970-IMG_20170526_161012.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4779481/original/078495900_1710991316-muslim-women-using-misbaha-keep-track-counting-tasbih.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4634211/original/032362200_1698988303-Sunan_Ampel_Wikimedia_Commons.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2397593/original/046324900_1541051170-fire-1008926_960_720.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4679861/original/019499900_1702101069-Dajjal.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4262146/original/085381500_1671090332-pexels-alena-darmel-8164382.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3291093/original/097460500_1604903000-20201109-Donald-Trump-Kalah-Pilpres-AS_-Rupiah-Menguat-7.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/821812/original/003800400_1425461464-Tinder-8.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5086670/original/010622200_1736404465-1736397368003_perbedaan-antara-nabi-dan-rasul-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/4870158/original/034485500_1718943680-IMG_20240621_112107.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5387154/original/093125200_1761032963-ilustrasi_wudhu.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/813545/original/080167000_1424263004-neraka.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5387833/original/050532800_1761104918-Ibu_Hamil.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5365896/original/038624400_1759209807-VJBQ2SzBTK.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4990690/original/039762200_1730716919-cara-bayar-fidyah-puasa.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4104854/original/037203900_1659064080-6398519.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5151380/original/086607800_1741158200-pray-6268224_1280.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4976748/original/009737400_1729605432-WISUDA_AKBAR_TAHFIDZ_QURAN_PELAJAR_TANGERANG_MENGAJI_-PJ_WALIKOTA_11.jpg)










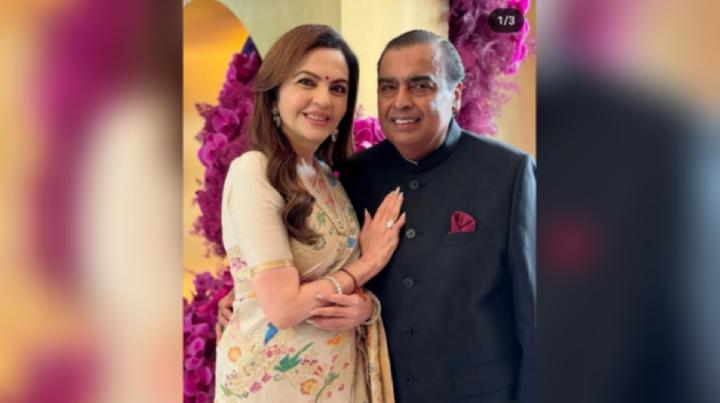









:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3110450/original/059507500_1587634731-Praying_Hands_With_Faith_In_Religion_And_Belief_In_God__Power_Of_Hope_And_Devotion___1_.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5264803/original/026336600_1750904581-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__11_.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/904568/original/070887100_1434622909-imagepemimpinresized.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5263442/original/009790100_1750822278-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__2_.jpg)