Liputan6.com, Jakarta - Masjid Menara Kudus merupakan salah satu wujud nyata akulturasi budaya antara Islam, Hindu, dan Buddha di Nusantara. Dibangun oleh Sayyid Ja'far Shodiq bin Syekh Sabil Sunan Ngudung Demak, lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus, pada tahun 956 H atau 1549 M, masjid ini menunjukkan kebijaksanaan Walisongo dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan menghargai budaya lokal.
Akulturasi budaya yang terwujud dalam Masjid Menara Kudus mencerminkan strategi dakwah kultural Sunan Kudus yang mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan masyarakat setempat. Pendekatan ini menjadikan Islam diterima dengan damai oleh masyarakat Jawa yang sebelumnya dipengaruhi budaya Hindu-Buddha.
Bahkan, dalam aspek sosial, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi sebagai bentuk empati terhadap umat Hindu, menggantinya dengan kerbau—sebuah tradisi yang masih bertahan hingga kini dalam kuliner khas Kudus.
Oleh karena itu, Masjid Menara Kudus tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol toleransi, persaudaraan, dan kecerdasan budaya dalam perjalanan sejarah penyebaran Islam di Indonesia.
Sejarah Masjid Menara Kudus
Masjid Menara Kudus adalah salah satu masjid tertua di Jawa dan menjadi situs penting bukti penyebaran Islam. Merujuk artikel berjudul 'Masjid Menara Kudus, Kemegahan Arsitektur Kuno Warisan Sunan Kudus' dan jurnal Peran Sosial Masjid Menara Kudus sebagai Pusat Keagamaan dan Budaya Lokal di Kudus karya Ahmad Muhctar Luthfi dkk. (2025), sejarah Masjid Menara Kudus berawal dari pendiriannya oleh Sunan Kudus pada tahun 956 H atau 1549 M.
Terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, masjid ini dibangun pada masa peralihan dari kejayaan Hindu–Buddha menuju penyebaran Islam di Jawa. Sunan Kudus menggunakan pendekatan dakwah yang damai dan akomodatif terhadap budaya lokal, sehingga masjid ini menjadi simbol keberhasilan strategi dakwah berbasis akulturasi.
Nama aslinya adalah Masjid Al-Aqsha, dan menurut tradisi lisan, batu pertama pembangunannya dibawa dari Baitul Maqdis (Yerusalem), yang kemudian menginspirasi nama daerah “Kudus”—berarti suci atau al-Quds.
Secara arsitektural, masjid ini memadukan gaya Islam dengan elemen Hindu–Buddha. Menara bata merah yang menyerupai candi menjadi bukti paling jelas dari proses akulturasi tersebut.
Bentuk menara itu dipilih agar masyarakat Hindu tidak merasa asing dan tetap akrab dengan simbol visual yang telah mereka kenal. Kompleks masjid juga mencakup makam Sunan Kudus, menjadikannya tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang ziarah dan pusat sosial-religius masyarakat.
Tradisi haul, tahlilan, dan ziarah yang terus berlangsung hingga kini memperkuat fungsi masjid sebagai pusat spiritual sekaligus sosial budaya. Dengan demikian, Masjid Menara Kudus bukan hanya monumen sejarah keislaman, melainkan juga simbol keberhasilan integrasi antara agama dan budaya lokal Jawa yang selaras dengan teori fungsionalisme agama Emile Durkheim mengenai peran institusi keagamaan dalam menjaga kohesi sosial
Arsitektur Masjid Menara Kudus
Arsitektur Masjid Menara Kudus (Masjid Al-Aqsha Manarat Qudus) merupakan salah satu contoh paling menonjol dari akulturasi budaya Islam, Hindu, dan Buddha di Nusantara.
Jurnal “Akulturasi Budaya Masjid Menara Kudus Ditinjau dari Makna dan Simbol” oleh Aufa Fasih Azzaki dkk. (UMS, 2021) mengungkapkan, arsitektur masjid ini mencerminkan strategi dakwah kultural Sunan Kudus yang menyebarkan Islam dengan cara menghargai dan menyerap elemen budaya setempat.
Masjid Menara Kudus merupakan hasil perpaduan harmonis antara arsitektur Islam dan gaya arsitektur lokal Jawa-Hindu-Buddha.
- Dari Islam: Muncul elemen seperti mihrab, kubah, kaligrafi, dan arah kiblat.
- Dari Hindu-Buddha: Diadopsi bentuk menara menyerupai candi, gapura paduraksa (gunungan), dan padasan delapan pancuran.
- Dari Jawa: Tampak pada atap tajug bertumpang dua, penggunaan saka guru kayu jati, serta teknik susunan bata tanpa semen
Arsitektur masjid ini menjadi simbol “Islam yang membumi di Nusantara”, bukan menolak budaya lama, tetapi mengislamisasinya melalui simbol-simbol yang familiar bagi masyarakat Kudus abad ke-16.
Arsitektur Masjid Menara Kudus merupakan warisan arsitektur sinkretik (campuran) yang menggambarkan kecerdasan budaya Sunan Kudus dalam mengharmonikan ajaran Islam dengan budaya lokal.
Bangunan ini tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, simbolik, dan sosial yang tinggi — menjadikannya ikon toleransi dan kebijaksanaan dakwah Walisongo serta mahakarya arsitektur Islam Nusantara.
Bagian-Bagian Masjid Menara Kudus
Bagian-bagian utama Masjid Menara Kudus menunjukkan sinergi antara fungsi religius, sosial, dan simbolik budaya. Setiap elemen, menara, gapura, atap tajug, padasan, hingga makam, tidak hanya berfungsi secara struktural, tetapi juga mengandung makna akulturasi, toleransi, dan spiritualitas Islam yang berpadu harmonis dengan kebudayaan Hindu-Buddha dan Jawa lokal.
Inilah yang menjadikan Masjid Menara Kudus ikon peradaban Islam Nusantara dan warisan budaya yang mendalam nilai filosofisnya.
1. Menara (Al-Manar)
Fungsi: Tempat mengumandangkan adzan, meletakkan bedug dan kentongan, serta simbol dakwah Sunan Kudus.
Ciri Arsitektur: Terbuat dari bata merah tanpa semen, dengan tinggi ±18 meter dan dasar 10×10 meter.
Struktur: Terdiri dari tiga bagian utama – kaki, badan, dan puncak – seperti struktur candi Hindu-Majapahit.
Bentuknya menyerupai candi sebagai wujud penghormatan terhadap budaya Hindu-Buddha agar masyarakat setempat merasa akrab dan tidak asing terhadap simbol-simbol Islam.
Puncak menara memiliki atap tajug bertingkat dua dari kayu jati dengan empat saka guru, simbolisasi dari dua kalimat syahadat dan fondasi keimanan Islam.
2. Gapura (Lawang Kembar)
Dua bentuk gapura ditemukan, yaitu Kori Agung (gunungan utuh) dan Gapura Bentar (gunungan terbelah).
Fungsi: Sebagai pintu gerbang pembatas antara ruang profan (dunia luar) dan ruang sakral (kawasan masjid).
Ciri Arsitektur: Bergaya Hindu-Bali dan Majapahit, dengan hiasan ukiran batu bermotif padma, sulur-suluran, dan geometris Islami.
Simbol peralihan spiritual menuju kesucian; harmoni antara simbol Hindu (gunungan) dan nilai Islam (tauhid).
3. Padasan Wudhu (Tempat Wudhu Delapan Pancuran)
Fungsi: Tempat bersuci sebelum sholat, terletak di sisi selatan kompleks masjid (tempat wudhu pria)
Ciri Khas: Terdiri dari delapan pancuran berbentuk kepala arca, yang masing-masing melambangkan konsep Buddha Asta Sanghika Marga (Delapan Jalan Kebenaran).
Makna: Menggambarkan perpaduan antara pembersihan diri secara fisik dalam Islam dan pembersihan batin dalam ajaran Buddha.
4. Bangunan Utama Masjid
Ruang utama (ruang sholat) dilengkapi empat saka guru (tiang utama) dari kayu jati besar sebagai penopang atap. Dindingnya dari bata merah bercat putih, menandakan kesucian dan kesederhanaan. Terdapat mihrab dan mimbar kayu ukir gaya arsitektur Walisongo.
Atap: Menggunakan tajug bertumpang dua dengan mustaka di puncaknya. Dimaknai sebagai simbol dua kalimat syahadat dan tauhid Allah SWT. Di serambi depan terdapat kubah besar dan dua kubah kecil bergaya Mughal India.
5. Serambi Masjid
Berfungsi sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan pengajaran agama.
Ciri Arsitektur: Memiliki pilar beton dan kayu berdiameter 15–35 cm. Dihiasi kaca patri bertulisan Asmaul Husna dan nama sahabat Nabi, serta ventilasi skylight di bawah kubah.
Makna: Simbol keterbukaan dan interaksi sosial antarumat, menggambarkan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.
6. Kompleks Makam Sunan Kudus
Kompleks makam terletak di sebelah barat masjid. Selain makam Sunan Kudus, istri, keturunannya, serta tokoh-tokoh penting seperti KH. Raden Asnawi, pendiri Madrasah Qudsiyyah dan tokoh NU.
Sebagai pusat ziarah dan spiritualitas, memperkuat fungsi masjid sebagai pusat keagamaan dan budaya lokal.
7. Halaman dan Ruang Sosial
Menjadi lokasi pelaksanaan tradisi Festival Dhandhangan (menyambut Ramadan) dan Buka Luwur (penggantian kain makam Sunan Kudus). Halaman depan juga berfungsi sebagai ruang publik keagamaan dan budaya, memperkuat makna sosial masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat Kudus. Kesimpulan
Makna Masjid Menara Kudus
Merujuk jurnal Peran Sosial Masjid Menara Kudus sebagai Pusat Keagamaan dan Budaya Lokal di Kudus, Masjid Menara Kudus dapat dipahami dari dua sisi utama, yaitu makna historis-religius dan makna simbolik-kultural hingga sosial-spiritual.
Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga manifestasi dari akulturasi, toleransi, dan kebijaksanaan dakwah Islam di tanah Jawa.
1. Makna Historis dan Religius
Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus (Syekh Ja’far Shadiq) pada tahun 956 H / 1549 M sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Kudus. Berdirinya masjid ini menandai masa penting dalam sejarah Islamisasi Jawa, di mana ajaran Islam mulai diterima luas melalui pendekatan damai dan akomodatif terhadap budaya lokal.
Sunan Kudus tidak menolak tradisi lama masyarakat yang masih kental dengan pengaruh Hindu-Buddha, melainkan mengislamisasinya secara halus. Hal ini tercermin dalam beberapa tindakan simbolis, seperti larangan menyembelih sapi (bentuk penghormatan terhadap keyakinan Hindu) dan pembangunan menara yang menyerupai candi, agar masyarakat tidak merasa terasing dengan simbol-simbol keagamaan yang baru.
Dengan demikian, secara historis Masjid Menara Kudus bermakna sebagai simbol keberhasilan dakwah damai dan inklusif Walisongo, serta bukti integrasi Islam dalam budaya Jawa tanpa menghapus identitas lokal.
2. Makna Simbolik dan Kultural
Makna mendalam dari Masjid Menara Kudus terletak pada simbol-simbol arsitekturnya, yang menggambarkan harmoni antaragama dan nilai-nilai multikultural:
Menara berbentuk candi melambangkan penyatuan Islam dan Hindu, menunjukkan bahwa Islam menghargai budaya yang telah ada sebelumnya.
Padasan wudhu dengan delapan kepala arca memiliki makna spiritual yang merujuk pada ajaran Buddha Asta Sanghika Marga (Delapan Jalan Kebenaran), melambangkan pembersihan diri dan perjalanan menuju kesucian, baik dalam perspektif Islam maupun Buddha.
Gapura paduraksa (lawang kembar) menjadi simbol peralihan dari ruang duniawi menuju ruang sakral, menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari alam profan menuju kedekatan dengan Tuhan.
Atap tajug bertumpang dua dimaknai sebagai simbol dua kalimat syahadat, yang menjadi fondasi utama keislaman.
Kaligrafi Asmaul Husna dan nama sahabat Nabi pada kaca patri kubah menegaskan identitas Islam yang berpadu dengan estetika Jawa.
3. Makna Sosial dan Spiritualitas
Selain itu, masjid ini juga memiliki makna sosial sebagai pusat kehidupan masyarakat Kudus. Ia menjadi tempat ibadah, pendidikan agama, serta pelestarian tradisi lokal seperti Festival Dhandhangan (menyambut Ramadhan) dan Buka Luwur (penggantian kain makam Sunan Kudus).
Melalui kegiatan tersebut, masjid ini berfungsi sebagai ruang integrasi sosial dan budaya, tempat masyarakat memperkuat identitas religius sekaligus kearifan lokal.
Pengaruh Masjid Menara Kudus
Berdasar jurnal Akulturasi Budaya Masjid Menara Kudus Ditinjau dari Makna dan Simbol, pengaruh Masjid Menara Kudus (Masjid Al-Aqsha Manarat Qudus) terhadap perkembangan arsitektur dan budaya masjid-masjid lain di Jawa sangat besar dan berperan penting dalam pembentukan identitas arsitektur Islam Nusantara.
Pengaruh tersebut dapat dijelaskan dari tiga aspek besar: arsitektur, budaya dakwah, dan fungsi sosial-keagamaan.
1. Pengaruh dalam Arsitektur Masjid di Jawa
Masjid Menara Kudus menjadi model arsitektur peralihan dari pengaruh Hindu-Buddha ke gaya arsitektur Islam di Jawa. Banyak masjid setelah abad ke-16 meniru atau mengadaptasi bentuk dan filosofi arsitekturnya, seperti:
a. Bentuk Atap Tajug Bertumpang
Ciri atap tajug (berlapis dua atau tiga) dengan saka guru (empat tiang utama) dari kayu jati menjadi ciri khas masjid tradisional Jawa.
Gaya ini diikuti oleh Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Sendang Duwur (Lamongan), Masjid Mantingan (Jepara), dan Masjid Agung Cirebon.
Simbolisme dua atau tiga lapis atap diartikan sebagai tingkatan spiritual menuju tauhid, sementara puncak mustaka melambangkan puncak keesaan Allah.
b. Menara dan Gapura Bergaya Candi
Menara Kudus menjadi inspirasi bagi banyak masjid di Jawa yang kemudian membangun menara berbentuk candi bata merah, misalnya:
Masjid Agung Banten dengan menara mirip mercusuar dan ornamen bata merah,Masjid Sendang Duwur (Lamongan) dengan menara bata berpola Hindu-Jawa, Masjid Mantingan (Jepara) yang juga menggunakan gapura paduraksa khas Majapahit.
Elemen gapura bentar dan kori agung di kompleks masjid di Jawa Tengah dan Jawa Timur memperlihatkan pengaruh langsung dari rancangan Masjid Menara Kudus.
c. Penggunaan Material Lokal
Sunan Kudus mempopulerkan teknik bata merah tanpa semen (tradisi Majapahit), yang kemudian diadopsi oleh masjid-masjid lain di pantai utara Jawa.
Teknik ini tidak hanya efisien tetapi juga menjadi simbol kesederhanaan dan ketahanan budaya lokal terhadap perubahan.
2. Pengaruh terhadap Strategi Dakwah dan Toleransi
Masjid Menara Kudus bukan hanya memengaruhi bentuk fisik masjid, tetapi juga cara dakwah Islam di Jawa. Sunan Kudus menerapkan strategi dakwah kultural, yaitu penyebaran Islam dengan menghargai budaya Hindu-Buddha dan tradisi Jawa.
Pendekatan ini kemudian diikuti oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Muria, yang menggunakan simbol budaya lokal (wayang, gamelan, arsitektur, dan seni ukir) untuk memperkenalkan Islam
Masjid-masjid yang dibangun setelahnya menjadi pusat dakwah dan budaya, bukan hanya tempat salat.Prinsip dakwah damai ini membentuk karakter Islam Jawa yang toleran, adaptif, dan humanis, yang bertahan hingga kini di banyak daerah.
3. Pengaruh Sosial dan Kultural
Masjid Menara Kudus juga menjadi model integrasi antara fungsi ibadah dan sosial-budaya, yang mengilhami banyak masjid di Jawa:
Masjid bukan hanya pusat ritual, tetapi juga pusat pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Tradisi haul, buka luwur (penggantian kain makam wali), dan dhandhangan (penyambutan Ramadan) menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat dan kini juga dilakukan di daerah lain.
Pola ini menunjukkan bahwa masjid di Jawa berfungsi sebagai simpul spiritual dan sosial, meneruskan jejak Masjid Menara Kudus yang menjadi tempat ziarah, pembelajaran agama, dan pelestarian tradisi.
4. Pengaruh Filosofis dan Simbolik
Arsitektur Masjid Menara Kudus membawa pesan simbolik universal yang diikuti banyak masjid tradisional Jawa:
Gapura = peralihan dari dunia fana menuju ruang suci.Padasan delapan pancuran = pembersihan diri jasmani dan rohani.
Atap tajug = tauhid dan syahadat.
Saka guru = empat sahabat Nabi (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali).
Nilai simbolik ini kemudian menjadi “bahasa arsitektur dakwah” bagi pembangunan masjid-masjid di seluruh Jawa, dari pesisir hingga pedalaman.
People also Ask:
1. Masjid Menara Kudus dibangun oleh siapa?
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah | Destinasi Wisata | MASJID ...Menara Masjid Kudus memiliki unik arsitektur menggabungkan arsitektur Jawa - Hindu - Islam.
Menara ini terbuat dari merah batu bata dengan ketinggian sekitar 17 m. Kuno Masjid Kudus dibangun pada tahun 1685 oleh Syeh Jafar Shodiq (Sunan Kudus).
2. Mengapa Masjid Menara Kudus disebut sebagai wujud akulturasi budaya?
Hal itu karena terdapat batu pertama pendirian masjid yang berasal dari palestina. Bangunan masjid tersebut memiliki konsep yang berbeda dengan bangunan disekelilingnya yang kebanyakan diadaptasi dari budaya Hindu.
3. Apa yang menjadi ciri khas Masjid Kudus?
Masjid Menara Kudus memiliki bagian penting yang punya makna sejarah. Menara kudus paling penting sekaligus ciri khas dan keunikan masjid ini.
Dibangun dari bata merah dengan gaya arsitektur khas Hindu-Buddha yang menyerupai candi. Menara ini berfungsi sebagai tempat adzan sekaligus simbol toleransi Islam.
4. Masjid Kudus peninggalan kerajaan apa?
Sejarah Masjid Menara Kudus, Simbol Akulturasi Budaya dan ...Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang pernah meruntuhkan Kerajaan Majapahit.
Sunan Kudus kemudian mendirikan sebuah masjid dengan akulturasi budaya Hindu-Jawa dengan Islam agar masyarakat lokal dapat menerima kehadiran Islam dengan baik.
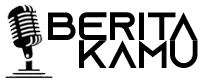
 2 days ago
7
2 days ago
7
:strip_icc()/kly-media-production/promo_images/1/original/085223300_1761037787-Desktop_1280_x_190.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5082269/original/032884500_1736233897-1736231251952_flexing-itu-apa.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3433074/original/r-view-beautiful-asian-muslim-woman-wearing-white-sleepwear-stretching-her-arms-after-getting-up-morning-sunrise-cute-young-girl-with-blue-hijab-standing-relaxing-while-looking-away_44289-1276__1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4628436/original/095598200_1698637528-8712637.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3954600/original/001373400_1646637027-3110.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/930717/original/070541900_1437079645-sunan-kalijaga-wartamadani.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5169862/original/050122900_1742550938-pexels-shukran-2103130.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4262146/original/085381500_1671090332-pexels-alena-darmel-8164382.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5142778/original/047144800_1740471441-pexels-mikhail-nilov-9783906.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5365524/original/054763800_1759199598-Wanita_muslim_membaca_buku_di_kasur.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5365523/original/042845000_1759199598-Dua_wanita_muslimah_membaca_buku.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5391374/original/020932200_1761311781-pant4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5380435/original/008084100_1760424585-Pria_berdoa_setelah_sholat__Pexels_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4975694/original/033193500_1729565937-nama-wali-songo.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/930714/original/070224300_1437079645-sunan-giri.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/930718/original/070650000_1437079645-sunan-muria-kabarmakkah.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1935315/original/054978200_1519567737-Topeng_Losari_Berusia_Ratusan_Tahun.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1634728/original/051392600_1498556758-1__rain-316580_960_720__Pixabay.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/930720/original/2cda8888ff3dd5f06447f220aa1aec02-desabebel.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5167593/original/083515700_1742364471-Kesehatan_mata.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4817795/original/081213100_1714478080-MALAIKAT_-_ISLAM_POPULER_2.JPG)





























