Liputan6.com, Jakarta - Wali Songo secara harfiah berarti sembilan wali adalah tradisi kolektif yang merujuk pada sembilan ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 sampai ke-16. Istilah dan daftar sembilan wali ini terutama berkembang dalam tradisi sastra Jawa (babad) dan tradisi lisan.
Merujuk Karya Ilmiah berjudul 'Wali Songo dalam Pentas Sejarah Nusantara oleh Prof. Dr. Budi Sulistiono (UIN Jakarta), Wali Songo menempati posisi sentral dalam perjalanan sejarah Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai pembaru sosial dan kultural pada masa transisi dari kerajaan Majapahit menuju era Kesultanan Demak.
Dakwah dilakukan secara damai, menyesuaikan diri dengan konteks sosial masyarakat Jawa kala itu. Hal ini menjadikan proses Islamisasi berlangsung tanpa kekerasan, melainkan melalui pendidikan, perdagangan, dan pendekatan budaya yang akomodatif. Di kemudian hari, model inilah yang menjadi dasar wajah Islam Nusantara yang inklusif.
Keberhasilan Wali Songo bertumpu pada strategi sosial, ekonomi, dan politik yang cerdas. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menggerakkan masyarakat melalui sistem pendidikan pesantren, perdagangan rakyat, hingga pembangunan struktur pemerintahan berbasis nilai Islam.
Daftar Nama-Nama Wali Songo
Merujuk jurnal “Treading the Footsteps of Wali Songo as The Shaper of Islam Nusantara Tradition” (Siti Muliana & Muhammad Nasruddin), Makalah “Wali Songo dalam Pentas Sejarah Nusantara” (Prof. Dr. Budi Sulistiono, UIN Syarif Hidayatullah), dan jurnal “Konsep Kultural Dakwah Walisongo Memperkuat Moderasi Beragama” (Achmad Wildan Khoerun Nahar, UIN Walisongo Semarang), seluruh Wali Songo menjalankan dakwah dalam rentang waktu sekitar 1390 hingga 1568 M, membentang dari Gresik hingga Cirebon. Mereka menghadirkan Islam dengan wajah yang damai, kultural, dan berkeadaban
Berikut ini adalah daftar sembilan wali (Wali Songo) mencakup riwayat singkat, daerah dakwah, perkiraan tahun, dan model dakwah masing-masing tokoh.
1. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)
Berda’wah di wilayah Gresik, Jawa Timur, sekitar 1390–1419 M, Sunan Gresik dikenal sebagai pelopor Islamisasi di tanah Jawa. Ia datang melalui jalur perdagangan internasional dan memulai dakwah dengan pendekatan sosial dan pendidikan.
Ia mendirikan tempat belajar, mengobati masyarakat secara gratis, dan menanamkan nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata, bukan perdebatan teologis. Model dakwahnya menonjol dalam aspek pelayanan kemanusiaan dan keteladanan moral.
Dari Gresik inilah benih penyebaran Islam di Jawa tumbuh dengan cara damai dan berakar di masyarakat pesisir.
2. Sunan Ampel (Raden Rahmat)
Dakwahnya berpusat di Surabaya dan Ampel Denta sekitar 1440–1481 M. Sunan Ampel membangun sistem pendidikan Islam pertama di Jawa melalui pendirian pesantren yang kemudian menjadi model dasar lembaga keislaman Nusantara.
Melalui pendidikan, ia membentuk generasi ulama seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang. Dakwahnya menekankan pentingnya ilmu, akhlak, dan ketertiban sosial.
Ia juga turut mempersiapkan dasar berdirinya Kesultanan Demak, menjadikan perannya strategis dalam pembentukan struktur sosial-politik Islam di Jawa.
3. Sunan Bonang (Raden Maulana Makdum Ibrahim)
Berda’wah di Tuban dan Lasem sekitar 1460–1525 M, Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh kreatif yang memperkenalkan dakwah melalui seni dan budaya. Ia menciptakan tembang-tembang religius seperti Tombo Ati dan menggunakan gamelan sebagai sarana mengenalkan nilai-nilai Islam.
Pendekatannya menyentuh aspek estetika masyarakat Jawa, mempertemukan ajaran tasawuf dengan keindahan budaya lokal.
Model dakwah kultural ini menjadikan Islam mudah diterima, sekaligus memperkuat tradisi spiritual yang lembut dan mendalam.
4. Sunan Drajat (Raden Qasim)
Aktif di Lamongan, Jawa Timur, sekitar 1470–1520 M, Sunan Drajat dikenal dengan dakwah sosialnya yang berorientasi pada kemanusiaan.
Ia menekankan pentingnya solidaritas, sedekah, dan tolong-menolong sebagai wujud keimanan. Dalam pengajarannya, ia sering menyampaikan pesan moral melalui tembang dan peribahasa Jawa yang sarat nilai sosial.
Model dakwahnya bersifat humanis—menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari ibadah. Dengan cara ini, Islam tampil sebagai ajaran yang membebaskan masyarakat dari kesengsaraan sosial dan ekonomi.
5. Sunan Kudus (Ja’far Shadiq)
Berdakwah di Kudus, Jawa Tengah, pada sekitar 1480–1550 M, Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memadukan kekuasaan dan kebudayaan. Ia mendirikan Masjid Menara Kudus dengan arsitektur khas perpaduan Hindu-Jawa-Islam.
Pendekatannya mencerminkan toleransi tinggi terhadap masyarakat Hindu-Buddha. Dalam dakwahnya, ia mengedepankan penghormatan terhadap keyakinan lama sambil memperkenalkan nilai tauhid secara halus.
Model dakwahnya bersifat kultural-toleran, memperlihatkan Islam yang menghargai perbedaan dan mengajarkan harmoni sosial.
6. Sunan Giri (Raden Paku / Ainul Yaqin)
Berdakwah di Giri, Gresik, sekitar 1480–1506 M, Sunan Giri mendirikan pusat pendidikan Islam yang dikenal sebagai Giri Kedaton.
Dari tempat ini, dakwahnya meluas hingga Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Ia dikenal sebagai pemimpin spiritual dan politik yang menggabungkan keilmuan dengan kepemimpinan moral.
Sistem pendidikan yang ia bangun menanamkan ajaran Islam berbasis ilmu, disiplin, dan etika sosial. Model dakwahnya bersifat institusional dan visioner, mengintegrasikan dakwah dengan pembangunan peradaban.
7. Sunan Kalijaga (Raden Said)
Berdakwah di Demak, Kadilangu, dan pesisir Jawa Tengah sekitar 1470–1520 M, Sunan Kalijaga adalah figur sentral dakwah kultural di Jawa.
Ia menggunakan kesenian seperti wayang kulit, tembang suluk, dan simbol-simbol budaya Jawa untuk menanamkan ajaran Islam. Kalijaga menekankan makna spiritual di balik tradisi lokal, menjadikan Islam tidak bertentangan dengan adat, melainkan melengkapinya.
Model dakwahnya akomodatif dan kreatif, memperlihatkan bagaimana Islam bisa tumbuh tanpa menghapus identitas budaya masyarakat.
8. Sunan Muria (Raden Umar Said)
Pusat dakwahnya berada di Gunung Muria, Jepara, dan Pati, sekitar 1500–1550 M. Sunan Muria dikenal dekat dengan masyarakat desa dan nelayan.
Ia mengajarkan ajaran Islam melalui kehidupan sehari-hari—pertanian, perdagangan, dan gotong royong. Dakwahnya sederhana, tetapi mengakar dalam kesadaran sosial masyarakat bawah.
Model dakwahnya disebut dakwah kerakyatan, yang menghubungkan ajaran Islam dengan realitas hidup rakyat kecil. Melalui pendekatan ini, Islam hadir bukan sebagai doktrin, melainkan pedoman hidup yang membumi.
9. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)
Berdakwah di Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa, sekitar 1470–1568 M, Sunan Gunung Jati menjadi tokoh yang menggabungkan spiritualitas dan kekuasaan.
Ia mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di Jawa Barat. Dakwahnya menekankan kepemimpinan moral, keadilan sosial, dan pembinaan masyarakat melalui struktur pemerintahan.
Model dakwahnya bersifat politik-religius, di mana kekuasaan digunakan bukan untuk memaksa, melainkan membimbing. Melalui kepemimpinan yang bijak, Islam tumbuh menjadi kekuatan moral dan budaya di wilayah barat Nusantara.
Wali Songo dan Pembentukan Tradisi Islam Nusantara
Dalam kajian Siti Muliana dan Muhammad Nasruddin, 'Treading The Footsteps of Wali Songo as The Shaper of Islam Nusantara Tradition, Wali Songo dipandang bukan hanya sebagai tokoh keagamaan, melainkan arsitek utama terbentuknya Islam Nusantara.
Mereka berperan sebagai jembatan peradaban yang memadukan ajaran Islam dengan kultur lokal tanpa menimbulkan konflik sosial.
Proses Islamisasi yang dilakukan Wali Songo tidak berlangsung melalui penaklukan, melainkan lewat asimilasi budaya, pendidikan, dan moral sosial.
Peneliti menjelaskan bahwa Islam yang diajarkan Wali Songo bersifat substansial, menekankan nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang, bukan formalisme syariat semata.
Dalam konteks itu, Islam hadir sebagai etika kehidupan, bukan simbol politik. Pendekatan semacam ini yang kemudian melahirkan wajah Islam Nusantara: damai, terbuka, dan berakar kuat dalam kebudayaan setempat.
Wali Songo memanfaatkan tradisi lokal seperti gamelan, wayang, hingga upacara adat sebagai media dakwah, dengan tujuan agar Islam terasa “milik bersama”, bukan ajaran asing yang memutus masa lalu masyarakat Jawa.
Wali Songo dalam Lintasan Sejarah
Prof. Dr. Budi Sulistiono, menempatkan Wali Songo secara kronologis sebagai aktor kunci transisi peradaban Jawa dari era Majapahit menuju Demak. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai penyebar agama, tetapi juga pembaru sosial, politik, dan ekonomi.
Menurut Sulistiono, dakwah Wali Songo berlangsung sepanjang akhir abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-16, berpusat di jalur pesisir utara Jawa yang menjadi simpul perdagangan internasional saat itu.
Keberhasilan dakwah para wali sangat dipengaruhi oleh strategi sosial dan ekonomi yang terukur. Sunan Gresik, misalnya, membangun basis ekonomi umat melalui perdagangan dan pertanian, sementara Sunan Ampel dan Sunan Giri mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam.
Adapun Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang memainkan peran kultural, mengolah kesenian lokal menjadi sarana dakwah. Dari sisi politik, Sunan Gunung Jati menegakkan pemerintahan Islam di Cirebon yang berperan sebagai model tata kelola berbasis syariat dan kearifan lokal.
Wali Songo adalah pilar yang menegakkan fondasi masyarakat Islam di Jawa. Mereka memperlihatkan bahwa Islam bisa berkembang tanpa menghapus tradisi, melainkan mengislamkan budaya itu sendiri.
Dengan demikian, lahirlah tatanan sosial baru yang tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan Nusantara.
Dakwah Kultural dan Moderasi Beragama
Achmad Wildan Khoerun Nahar dalam Jurnal Konsep Kultural Dakwah Walisongo Memperkuat Moderasi Beragama menyoroti sisi teoretis dari dakwah Wali Songo sebagai model moderasi beragama. Wali Songo menggunakan pendekatan dakwah kultural-akomodatif, yakni metode yang menyesuaikan penyampaian ajaran Islam dengan konteks sosial-budaya masyarakat.
Prinsip utama pendekatan ini adalah maw’izhatul hasanah, mengajak dengan nasihat yang lembut, memberi keteladanan, serta menghindari sikap konfrontatif terhadap tradisi lama.
Setiap wali memiliki spesialisasi dakwah yang saling melengkapi. Sunan Gresik dikenal sebagai pendidik dan pedagang yang menekankan kesejahteraan sosial; Sunan Ampel menata hukum dan etika Islam melalui pendidikan pesantren; Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga mengangkat seni, simbol, dan kesusastraan Jawa untuk memperkenalkan nilai Islam; sementara Sunan Gunung Jati memperkuat struktur politik Islam melalui pemerintahan.
Semua metode ini berpangkal pada satu semangat, menghadirkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam yang menebarkan kedamaian bagi semua.
Dakwah Wali Songo memperlihatkan model Islam moderat yang menolak ekstremisme. Islam tidak tampil sebagai kekuatan pemaksa, melainkan sebagai nilai moral yang membimbing perubahan.
Karena itulah, pendekatan Wali Songo relevan dalam konteks kontemporer Indonesia, terutama dalam memperkuat gerakan moderasi beragama yang kini menjadi agenda nasional.
People Also Ask:
1. 9 Wali Songo itu siapa saja?
Sembilan nama Wali Songo adalah Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim), Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Giri (Raden Paku/Muhammad Ainul Yaqin), Sunan Bonang (Makhdum Ibrahim), Sunan Drajat (Raden Qasim), Sunan Kudus (Ja'far Shadiq), Sunan Kalijaga (Raden Said), Sunan Muria (Raden Umar Said), dan Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah).
2. 9 Sunan dimana saja?
Makam Sembilan Wali Songo tersebar di pulau Jawa, dengan rincian: lima di Jawa Timur (Gresik, Surabaya, Tuban, Lamongan), tiga di Jawa Tengah (Demak, Kudus, Muria), dan satu di Jawa Barat (Cirebon). Secara spesifik, lokasinya adalah: Sunan Gresik (Gresik), Sunan Ampel (Surabaya), Sunan Giri (Gresik), Sunan Bonang (Tuban), Sunan Drajat (Lamongan), Sunan Kalijaga (Demak), Sunan Kudus (Kudus), Sunan Muria (Kudus), dan Sunan Gunung Jati (Cirebon).
3. Wali 9 keturunan siapa?
Wali Songo memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yang silsilahnya tersambung melalui putri Nabi, Sayyidah Fathimah Az-Zahra, dan menantu beliau, Ali bin Abi Thalib. Para wali ini umumnya adalah keturunan para habaib dari marga Adzmatkhan yang berasal dari Yaman (Hadramaut).
4. Apakah Syekh Maulana Maghribi termasuk Wali Songo?
Sayyid Maulana M. Al-Maghribi, atau yang dikenal sebagai Syekh Maghribi (1321-1465) salah satu walisongo. Nama Beliau juga tercatat sebagai Anggota Dewan Walisongo Senior (Angkatan Pertama). Makam anggota senior Wali Songo ini berada di Kota Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di kompleks Kesultanan Kanoman.
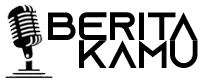
:strip_icc()/kly-media-production/promo_images/1/original/085223300_1761037787-Desktop_1280_x_190.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4289354/original/041089600_1673516524-arabic-desserts-near-books.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5507818/original/092628300_1771554129-kubah_masjid.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2220482/original/035724700_1526813013-The_Blue_Mosque_at_night.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1251419/original/001109600_1464774480-tower-BNI-6.original.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4552319/original/085794300_1693014233-000_33TB22J.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5176139/original/066062200_1743063964-5b5fd754-75c6-4c6c-917f-abb65a3ff338.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5508989/original/009754500_1771646627-tempat_makan_dekat_stasiun_senen5.webp)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3419757/original/096492500_1617596681-IMG_7389.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5509462/original/015878700_1771715680-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5508149/original/000933100_1771567036-ivan.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5507282/original/042303900_1771488416-611690465_18551369515039800_5623139189157550141_n.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5509210/original/054924500_1771663566-Koleksi_dari_Zaskia_Mecca.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5371443/original/090307800_1759655308-000_77QL4RK.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4396549/original/031093700_1681559154-pexels-thirdman-7956663.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5508703/original/056868800_1771587285-Gemini_Generated_Image_bf0ew7bf0ew7bf0e.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5503059/original/016909700_1771077116-Player_Best_Moment_By_Antangin_Ayo_Jol__Lebih_baik_di_babak_kedua__Persebaya__Persebayauntuksemu__1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5508860/original/044428500_1771630300-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5507759/original/025480600_1771548984-Booyah_Ramadan_Free_Fire_2026_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5296575/original/005879800_1753595807-1000091385.jpg)




















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5348709/original/090969100_1757859256-bioskop.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5428698/original/015580400_1764559226-Kalender_HIjriah_Desember_2025.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4010689/original/086569000_1651202668-pexels-rayn-l-3163677.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4975694/original/033193500_1729565937-nama-wali-songo.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1554094/original/040157900_1491121330-stairs-735995_1920.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4688353/original/005421400_1702706741-pertengkarabn_suami_istri_telisik.com_.jpg)